Interograsi
Meskipun jarum arlojiku sudah melewati angka sembila dan berhenti di enam belas menit, suara derit kipas dinding itu terus memecah kesunyian, ia bergerak malas ke kanan, lalu ke kiri. Hawa panas menempel di kulit, membuat kausku terasa lembap. Di luar sana hujan mengguyur tanpa ampun, tapi ruangan ini tetap pengap. Seolah udara telah terkunci bersama ribuan napas para penjahat yang pernah masuk dan keluar dari sini.
Mataku menyapu seisi ruangan, kecil, mungkin luasnya tak beda jauh dengan kamar kos lamaku. dindingnya putih pucat, tanpa jendela, hanya satu pintu besi yang terlihat berat dan kedap suara. di pojok atas, sebuah CCTV menatapku tanpa berkedip. Siapa pun yang mengendalikan kamera itu, mungkin sedang memperhatikanku sekarang. Aku menarik napas panjang, membenarkan posisi dudukku. remaja sepertiku harus pandai menjaga kesan, bukan? Bukankah itu yang kita lakukan, berusaha terlihat baik di mata orang lain?
Aku sudah terjebak di sini selama tiga puluh menit. Waktu berjalan lambat, seperti jarum detik yang sengaja diseret paksa. Telapak tanganku terasa perih, kulitnya memerah dengan luka bakar yang tampak segar, berdenyut setiap kali aku mencoba mengepalkannya. Sakitnya membuatku ingin mengutuk, tapi bibirku hanya diam rapat.
Di seberang ruangan, kaca besar itu menampakkan bayangan seseorang dengan kaos hitam. Rambutnya yang panjang menutupi pelipisnya, Ia duduk kaku di kursi interogasi, kepalanya sedikit menunduk, namun pandangannya terpatri ke depan. Sesekali, sorot lampu redup membuat wajah itu samar seperti hantu yang terperangkap di balik kaca.
Kepalaku berdenyut ketika ingatan tadi kembali menghantam, langkah kaki, jeritan singkat, bau hangus… Semuanya bercampur menjadi satu, menghantui seperti film yang terus diputar ulang tanpa henti.
Teresa bukan tipe gadis yang membuat kepala orang-orang menoleh saat ia lewat. Dia bukan mahasiswi populer dengan penggemar di mana-mana, tapi juga bukan kutu buku yang menghabiskan hari-harinya di pojok perpustakaan, dia biasa saja. Justru mungkin karena itulah dia menarik perhatianku.
Aku masih ingat pertemuan pertama kami di koridor kampus. lantai licin karena gerimis tadi pagi, dan langkahnya pelan-pelan, seperti takut terpeleset. Rambutnya yang dikuncir seadanya bergerak sedikit setiap kali ia menunduk untuk memastikan buku-buku di pelukannya tidak jatuh. Saat pandangan kami bertemu, ada sesuatu di wajah lugunya, bukan sekadar polos, tapi memancarkan arti yang sulit dijelaskan.
“Eh, kita sekelas kan?” Aku akhirnya bertanya, pertanyaan klise yang keluar begitu saja.
Teresa mengangkat kepalanya, sedikit ragu tapi matanya langsung menatapku. Dia mengiyakan jawabnya pelan, senyumnya samar, seolah ia sendiri masih belajar bagaimana caranya bersikap hangat pada orang asing.
Dari situ aku mengetahui bahwa namanya adalah Teresa, kilas balik singkat cikal bakal bagaimana kami menjadi teman dekat. Layaknya seorang teman, dia sering membantuku mengerjakan tugas, begitupun sebaliknya. Saat ada tugas kelompok, tidak jarang kami selalu satu kelompok. Kami juga saling mengenal satu sama lain, saat satu minggu berturut-turut, dia selalu memesan satu makanan yang sama di kantin. Dari situ aku tahu bahwa Soto Santan adalah makanan kesukaannya.
Sebagai anak kos yang merantau di kota orang, aku dan Teresa akan menerima uang dari orang tua kami di tanggal yang sama di awal bulan. Suatu kebetulan bagi dua orang teman dekat, bukan? Untuk merayakannya, kami datang ke kedai kopi untuk memesan minuman, kemudian bertukar satu sama lain, kadang kejahilanku membelikannya Americano membuat ia tidak berhenti melepehkan kopi pahitnya. Sungguh sesuatu yang menyenangkan mempermainkan gadis lugu itu.
Tidak terlintas di benakku bahwa gadis yang terlihat polos ini akan melakukan hal yang sangat mengerikan.
Seminggu sebelum kejadian itu terjadi, tidak biasanya kursi di samping ku diisi mahasiswa lain, Teresa membolos seharian dan tidak bisa dihubungi. Kucoba meneleponnya disela-sela kelas berlangsung, berharap mendapat jawaban dari berbagai hantaman tanda tanya di kepalaku, namun jawaban itu malah datang dari operator yang monoton. Jawaban yang membuatku muak hingga aku ingin melempar ponselku sendiri.
Butuh waktu lama menunggu hingga kelas ini berakhir, apalagi kekhawatiran terus mendobrak jantungku. Tidak bisa ditahan sehingga saat kelas berakhir, aku langsung tancap gas menuju kosnya. Kunci cadangan yang kami tukar beberapa waktu lalu terasa dingin di genggamanku. Begitu pintu terbuka, aroma kamar Teresa langsung menyergap, wangi pengharum ruangannya masih sama seperti sebelumnya saat aku kemari, hanya saja lebih gelap, pencahayaan sangat minim, netraku menyisir tiap sisi ruangan berharap menemukan gadis yang kucari cari sedari tapi.
“Teresa?” Suaraku pelan, hampir berbisik.
Dia duduk memeluk lutut di sudut kamar. rambutnya kusut seperti belum disentuh sisir sejak kemarin. Aku terpaku sejenak sebelum berlari ke arahnya. Matanya sembap, lingkar hitam menghiasi kelopaknya. Hidungnya kemerahan, basah oleh ingus yang belum sempat dia bersihkan. maskara yang menghitam di pipinya tampak seperti bekas aliran hujan di kaca jendela.
“Hai… kamu kenapa?” Aku berjongkok di hadapannya, mencoba mencari matanya yang enggan menatapku.
Mulai hari itu, Teresa bukan lagi Teresa yang kukenal. katanya hubungan dengan pacarnya yang hampir lima tahun kandas begitu saja, laki-laki itu berselingkuh dengan rekan kerjanya di kafe. aku melakukan apa yang dilakukan sahabat pada umumnya, memberi nasihat seadanya, menepuk bahunya, memastikan dia tahu bahwa aku ada untuknya. saat itu, dia tampak sedikit tenang. tapi ternyata … aku salah besar.
Keesokan paginya, dia muncul di kampus dengan wajah yang membuat dadaku menegang. blus putihnya kusut, ada aroma lembap yang menyeruak dari kain seperti pakaian setengah kering yang terlalu lama ditumpuk. rambutnya awut-awutan, seolah belum bersentuhan dengan sisir sejak kemarin. mata sembap, itu masih sama seperti saat kutemui di sudut kamarnya.
“Ayo ikut aku.” Aku menarik lengannya, mengabaikan tatapan heran mahasiswa lain. pagi itu kami berdua absen dari kelas.
Di kosnya, Teresa duduk di tepi ranjang. tangannya menggenggam ponsel erat-erat, bibirnya bergetar dengan kata-kata yang tak jelas.
“Aku capek, cape banget… kayaknya nggak ada gunanya lagi semua ini.” Suaranya serak, hampir seperti bisikan.
Aku meraih ponselnya, berjaga-jaga kalau dia mencari cara melarikan diri lagi. di layar, riwayat pencarian membuat darahku berdesir: “cara membuat simpul gantung diri” terpampang jelas di baris teratas.
“Eh, Teresa… kok bisa mikirin hal segila ini?” suaraku meninggi tanpa sadar. aku memelototinya, tubuhku gemetar antara marah dan takut.
Dia tersentak, lalu menunduk dalam. “Maaf… nggak akan gitu lagi, maaf…,” ucapnya lirih, seperti anak kecil yang takut dimarahi. Hawa panas dalam dadaku perlahan mereda, digantikan dengan perasaan getir yang sulit dijelaskan.
Sejak hari itu, Teresa lenyap. Pemilihan kata yang kasar, tapi dia benar-benar menghilang, aku tidak pernah menyerah menghubunginya, kosnya terkunci rapat, entah dia sudah pindah atau dia enggan melihatku, namun setelah seminggu berlalu, dia dihadapanku sekarang. Di depan kedai kopi yang sama tempat kami menyeduh sebelum-sebelumnya. Dress putih sederhana membalut tubuh kecilnya, bukan gaun mewah, cuma kain katun yang jatuhnya lembut sampai ke lutut, tanpa motif, sedikit kusut di bagian bawah. Rambutnya diikat low ponytail, beberapa helaian kecil jatuh menutupi pipi dia abaikan terkibas anggun begitu saja.
“Nih.” Teresa menyuguhkan segelas kopi susu hangat diikuti dengan senyumnya yang begitu tulus.
“Kaya biasa, punyaku mana?” Senyumnya masih belum dia longgarkan.
Aku terpatri dengan kebimbangan, setelah seperti habis ditelan bumi, dia datang menyodorkan kopi susu murahan dengan tenang seperti tidak ada yang terjadi. Aku menyambut hangat senyumnya, menerima kopi dan memberi punyaku padanya. Daripada mengobati goresan tanda tanya di kepalaku. Aku memilih untuk membiarkan waktu berjalan, mungkin dia ingin melupakan semua kejadian yang lalu.
Saat semburat mentari berubah oranye, lampu-lampu jalan mulai menyala satu per satu, memantulkan cahaya redup di aspal basah. Aku dan Teresa masih menyantap bakso di pinggir jalan, kuah hangatnya tak berhasil menepis hawa dingin yang tiba-tiba merayap di tulang. langit di atas tampak abu-abu, seperti menyimpan sesuatu yang akan pecah kapan saja.
Mataku tertuju pada pemantik kecil yang sesekali ia putar-putar di antara jemarinya. Logam mungil itu memantulkan cahaya lampu jalan, membuat kilatan aneh di kulit pucat tangannya. Aku menahan napas sebentar, tapi buru-buru mengalihkan pandangan, berpura-pura tidak melihat apa-apa. Tas hitam besar yang tersampir di bahunya tampak tak sepadan dengan gaun putih sederhana yang ia kenakan, tas itu sedikit membebani punggungnya. Apa yang dia bawa? pikirku.
“Ayo pulang,” ucapnya pelan, bibirnya membentuk senyum tipis yang terasa asing. “Kali ini kita naik KRL.”
Di dalam kereta yang berderak pelan, kami duduk berdampingan. Tubuhnya sedikit membungkuk, dan tangannya tetap menggenggam sesuatu dengan erat. Aku mencuri pandang ke wajahnya, mata itu kosong, seperti kaca bening yang menyembunyikan riak-riak kecil di bawahnya. Lalu, dia berdiri. gerakannya pelan, nyaris seperti patung yang baru saja dipahat. Detik terasa panjang saat dia diam mematung, lalu dengan sekali tarikan ritsleting, dia mengeluarkan jeriken plastik dari ranselnya. isinya cairan bening kekuningan, aroma menyengat langsung menusuk hidungku.
“Teresa….” Suaraku tercekat, lidahku terasa kelu saat melihat jemarinya mulai melonggarkan tutup jeriken itu.
Dengan langkah mantap, Teresa menuangkan bensin ke lantai gerbong. Aroma menyengat langsung memenuhi udara, membuat penumpang menoleh, lalu saling berteriak panik saat cairan bening itu merambat cepat ke segala arah. Lantai kereta menjadi licin, beberapa orang tergelincir saat mencoba melarikan diri. Gerbong terus berguncang, suara otomatis terdengar dari pengeras suara —Tempat tujuan sebentar lagi sampai, mohon duduk dengan tenang— ironis di tengah kekacauan.
Orang-orang menjauhi Teresa seperti kawanan domba yang histeris melihat serigala. Aku sempat mengguncang tubuhnya, berharap gadis itu kembali sadar, tapi tubuhku ikut gemetar. Rasa takut mendorongku untuk menubruknya hingga kami terjatuh. Aku merangkak menjauh, telapak tanganku basah oleh genangan bensin yang berkilau di bawah cahaya redup.
Pemantik di tangannya berbunyi klik sekali, dua kali, percikan api tak kunjung muncul. Saat percikan ketiga berhasil, api langsung menyambar lantai, menjalar liar ke kursi-kursi. Kobaran itu menyebar cepat ke kanan dan kiri, teriakan penumpang menggema keras, disertai bau kain hangus yang menusuk hidung. Teresa berdiri goyah di tengah lautan api, tubuhnya terjerembab lagi ketika kakinya terpeleset. lidah-lidah api melahap gaun putihnya, menyelimuti tubuhnya hingga wujudnya hampir tak lagi terlihat.
Kabut hitam menggumpal membentuk sekat-sekat yang menghalang penglihatan, hanya cahaya api yang berkobar dan manusia-manusia diambang kematian yang terlihat samar. Hentakan kaki dan isakan kepasrahan menjadi alunan musik penghantar tidur menuju neraka. Saat kepasrahan itu hampir mencapai klimaks, pintu gerbong terbuka. Asap yang terkepung mulai mencuat dari berbagai arah. Orang-orang berlarian mencari udara segar. Sebagian tergeletak bersama gadis itu. Saat aku menoleh ke belakang, Teresa sudah mematung di sana. tubuhnya gosong, hitam hangus, tidak ada pergerakan lagi.
Semuanya sudah selesai.
Oke, nanti saat polisi bertanya, aku akan bilang seperti itu. Sungguh, jawaban yang luar biasa rapi, tidak akan ada yang curiga. Apapun yang terjadi, aku harus tetap tenang dan bicara dengan lancar. Jangan sampai terbata-bata, itu hanya akan membuat mereka berpikir aku berbohong. Mungkin aku akan menangis, membuat suara serak penuh kepanikan, atau … Pura-pura pingsan saja? Ah, terlalu dramatis. Haha, aku sampai tertawa sendiri.
Oh! itu dia, langkah sepatu dan suara walkie talkie mendekat. Polisi sudah datang. Semoga mereka tidak memeriksa sakuku … Ada pemantik di sana. sekarang waktunya memberi kesaksian.
 Julius Parker, bocah yang ngerasa umurnya mandek di angka 17, meskipun kalender terus jalan. Asalnya dari Kabupaten Kerinci, tempat di mana kabut pagi berasa kayak selimut alam. Suka ngelamun, bukan karena nggak ada kerjaan, tapi karena imajinasi sering ngajak dia jalan-jalan ke dunia yang lebih seru dari realita
Julius Parker, bocah yang ngerasa umurnya mandek di angka 17, meskipun kalender terus jalan. Asalnya dari Kabupaten Kerinci, tempat di mana kabut pagi berasa kayak selimut alam. Suka ngelamun, bukan karena nggak ada kerjaan, tapi karena imajinasi sering ngajak dia jalan-jalan ke dunia yang lebih seru dari realita


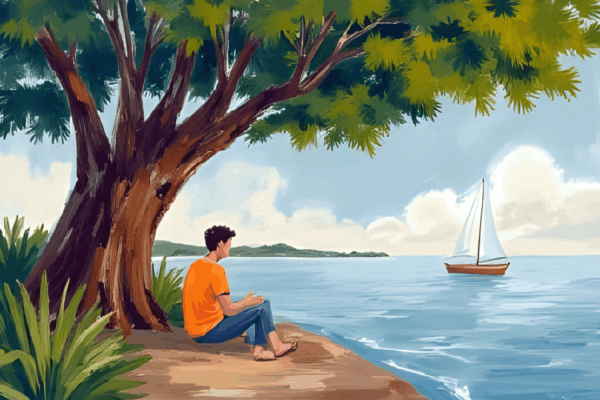


Juli 24, 2025 @ 2:14 pm
bagus bgtt, semangattt buat karya lagii si
Juli 24, 2025 @ 2:14 pm
semangattt buat karya lagii si
Juli 24, 2025 @ 2:17 pm
baguss bgtt, semanggat buat karya lagi sii